Dalam dinamika komunikasi politik Indonesia, perdebatan antara Hasan Nasbi dan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menjadi contoh menarik tentang bagaimana komunikasi publik dapat menjadi arena pertarungan makna dan citra. Hasan, yang dikenal sebagai mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di Podcast Total Politik melontarkan kritik tajam terhadap gaya bicara Purbaya yang dianggap terlalu terbuka dan cenderung “menyentil” pejabat lain. Menurutnya, gaya komunikasi semacam itu bisa melemahkan solidaritas antar pejabat dan menimbulkan kesan perpecahan di tubuh pemerintahan.
Dari perspektif komunikasi publik tindakan Hasan bisa dipahami sebagai bentuk metakomunikasi, komentar tentang cara berkomunikasi itu sendiri. Ia seolah mengingatkan bahwa komunikasi politik tidak hanya soal apa yang dikatakan, tetapi bagaimana dan kepada siapa pesan itu diarahkan. Dalam struktur komunikasi pemerintahan, setiap pernyataan publik seorang pejabat dapat menciptakan efek resonansi, baik di kalangan birokrasi maupun di tengah masyarakat. Hasan memposisikan dirinya sebagai pengingat agar komunikasi politik dijaga dalam bingkai kesatuan narasi pemerintah.
Namun, Purbaya tidak tinggal diam. Ia menanggapi kritik itu dengan cerdik melalui pendekatan berbasis data. Alih-alih membantah secara emosional, Purbaya menampilkan hasil survei yang menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Strategi ini secara komunikatif merupakan bentuk counter-framing yaitu mengalihkan fokus dari gaya komunikasinya ke hasil konkret yang bisa diukur. Dalam konteks teori komunikasi politik, langkah Purbaya dapat dikategorikan sebagai strategi penguatan kredibilitas (ethos appeal), yaitu mengandalkan fakta untuk mempertahankan citra positif.
Dari sudut pandang komunikasi organisasi, situasi ini menunjukkan adanya benturan antara idealisme internal dan kebutuhan eksternal. Ketika seorang pejabat mengkritik koleganya di depan publik, yang terjadi bukan hanya pertukaran opini, tetapi juga potensi munculnya fragmentasi citra pemerintah. Hasan menilai bahwa komunikasi internal seharusnya dijaga dalam ruang tertutup agar publik tidak menangkap kesan adanya perpecahan. Namun, di sisi lain, Purbaya justru memanfaatkan ruang publik sebagai arena transparansi dan legitimasi.
Menariknya, Purbaya membingkai gaya komunikasinya sebagai bentuk keberanian dan ketegasan, bukan sekadar spontanitas. Ia mengaku tidak pernah bertindak sendiri, melainkan dalam garis koordinasi dengan pimpinan tertinggi negara. Dari perspektif komunikasi kepemimpinan, pernyataan ini mengandung strategi simbolik: menunjukkan loyalitas sambil memperkuat kesan independensi. Ia berhasil memutar persepsi publik dari “gaya koboi” menjadi “gaya tegas berlandaskan mandat”.
Jika dianalisis melalui teori situasi komunikasi publik, perbedaan keduanya terletak pada pemilihan medium. Hasan menganggap bahwa kritik terhadap sesama pejabat sebaiknya dilakukan secara tertutup, sedangkan Purbaya percaya pada efektivitas ruang publik sebagai sarana membangun legitimasi dan transparansi. Pertarungan dua paradigma ini menggambarkan dilema klasik dalam komunikasi politik modern: antara kebutuhan menjaga harmoni internal dan tuntutan keterbukaan publik.
Dari aspek manajemen reputasi, langkah Purbaya menunjukkan upaya menjaga citra institusional dengan menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi. Dalam situasi semacam ini, pejabat publik sering kali dihadapkan pada dua pilihan: menanggapi kritik dengan defensif atau merespons dengan pembuktian. Purbaya memilih opsi kedua, yang secara teoritis lebih efektif dalam mempertahankan kepercayaan jangka pendek.
Namun, strategi ini juga menyimpan risiko. Jika gaya komunikasi yang terbuka dan keras terus dipertahankan tanpa pengelolaan narasi yang konsisten, publik bisa saja menangkap pesan ganda: di satu sisi tegas, di sisi lain terkesan arogan. Dalam komunikasi publik, persepsi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta. Karena itu, keberhasilan Purbaya dalam “menyudutkan balik” Hasan hanyalah kemenangan di tingkat wacana, bukan jaminan stabilitas persepsi jangka panjang.
Akhirnya, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana komunikasi di level pemerintahan tidak sekadar soal isi pesan, melainkan juga soal strategi membangun makna. Purbaya memang tampak berhasil “menyudutkan balik” Hasan dengan data dan narasi kuat, namun perdebatan mereka membuka refleksi lebih dalam bahwa kekuatan sejati komunikasi publik bukan pada siapa yang lebih vokal, melainkan siapa yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keharmonisan. Dalam kerangka komunikasi publik, “skakmat” sejati bukan saat lawan terdiam, melainkan ketika publik merasa yakin bahwa semua pihak tetap bergerak dalam satu irama tujuan.
Yons Achmad. Praktisi Komunikasi. Pendiri Brandstory.id







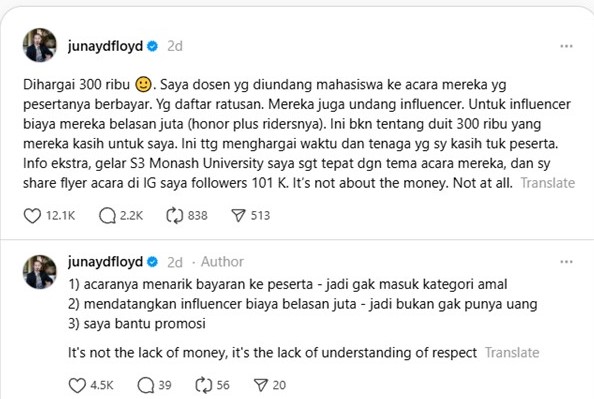


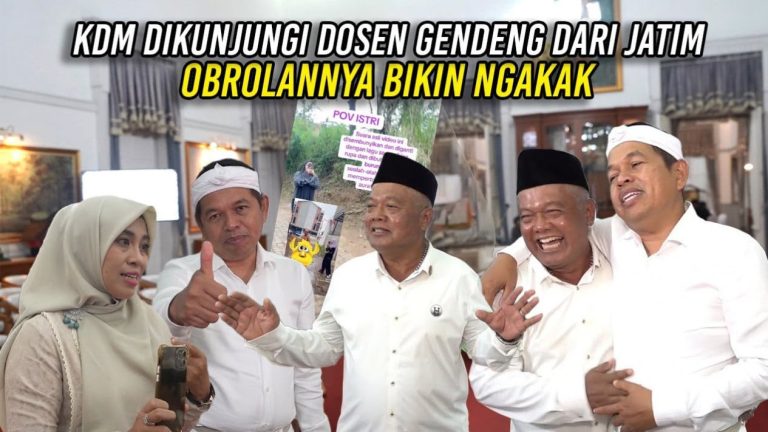






Comment